PENDAHULUAN
Dongeng Sangkuriang dalam berbagai versinya yang berkembang di masyarakat selalu menampilkan Dayang Sumbi, wanita yang melahirkan Sangkuriang terlahir dari babi dan ayahnya yang berupa anjing. Dongeng yang dihubungkan dengan mula terbentuknya Lembah Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu ini sering ditafsirkan sebagai bentuk peyoratif penolakan orang Sunda terhadap incest. Dongeng ini paralel dengan mitos Oedipus dari Yunani yang diambil oleh Freud untuk membangun teori Oedipus Complex-nya. Freud memang menegaskan bahwa mitos yang mengungkapkan seorang tokoh yang membunuh ayahnya dan mengawini ibunya ini muncul tidak hanya dalam satu kebudayaan saja. Juga terdapat banyak anggapan bahwa dongeng ini adalah bentuk totemisme kebudayaan Sunda primitif sebelum datangnya ajaran agama-agama. Tetapi gagasan ini mengidap kelemahan historis di dalamnya. Bersamaan dengan pengadaptasian kisah Mahabharata dan Ramayana dalam pewayangan berabad-abad lalu oleh para waliyullah dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, mustahil bila sebuah dongeng yang melukiskan konstruk masyarakat sangat primitif yang bertentangan dengan ajaran agama tetap dituturkan secara lisan di berbagai tempat di Tatar Sunda yang telah memeluk agama Islam sejak lama. Tak kurang dari seorang Haji Hasan Mustapa menyebut dongeng ini sebagai kisah suluk. Sangkuriang dipenuhi dengan simbol-simbol yang demikian kaya dan sepintas saling kontradiktif dalam dirinya itu, seperti babi dan anjing, air seni sang raja, gunung dan lembah, taropong, tempurung kelapa, ayam jago, dan boeh rarang. Hal itu menuntut kita untuk menolak dongeng itu secara keseluruhan karena sama sekali tidak beresonansi dengan kesadaran atau memperlakukannya sebagai wacana yang mengaktivasi ruang kecerdasan khusus. Vico, seorang filsuf Italia telah mengutarakan pendapat yang dikembangkan oleh Levi-Strauss bahwa masyarakat lampau memiliki suatu 'kebijakan-puitis' (sapienza poetica), di mana mereka menyatakan cara pandangnya terhadap dunia lewat berbagai bentuk metafisik metafora, simbol, dan mitos-mitos. Khasanah Sunda inilah yang akan merekonstruksi konsep strukturalisme budaya dan hakikat kemanusiaan yang membentuknya.
Semiotika, Strukturalisme dan Logostrukturalisme Bahasa Sunda
Istilah "semiotika" berakar dari bahasa Yunani, seme, semeion, juga semeiotikos, yang berarti penafsir tanda-tanda, kurang lebih arti semiotika adalah ilmu mengenai analisis tanda dan bagaimana sistem penandaan tersebut berfungsi. Semiotika menyeruak ke permukaan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mapan dan mengimbas banyak disiplin ilmu lainnya baru terjadi setelah para murid dan kolega Ferdinand de Saussure (1857-1913) menerbitkan buku Cours de Linguistique Générale secara anumerta pada tahun 1916 yang merupakan kumpulan catatan kuliah yang pernah diberikannya.
Saussure mendefinisikan tanda linguistik sebagai entitas dyadic di mana sisi pertama disebutnya dengan penanda (signifier), yaitu aspek material dari sebuah tanda entah berupa tulisan, suara maupun objeknya itu yang membentuk impresi mental. Sedang sisi keduanya adalah petanda (signified), yaitu abstraksi murni (pure abstract) yang sepenuhnya berupa konsep. Satu hal lagi yang sangat penting dalam kajian Saussure tentang tanda linguistik adalah sifat arbitrer yang menyatukan penanda dan petanda dimana tak ada logika yang ketat, alasan pasti yang menyatukan antara petanda dan penanda tak ubahnya dua permukaan kertas (retro dan verso).
Problem kearbitreran tanda Saussurian dapat disebabkan oleh dua hal berikut ini. Pertama, tidak dimengertinya proses pencerapan objek, baik yang berupa suara pengucapan dan tulisan pada kertas hingga terbentuk impresi mental yang berupa penanda (signifier) dan kedua, yang prosesnya sama sekali tidak teraba oleh semiotik, berupa pembentukan petanda (signified) yang berupa abstraksi murni. Problem yang pertama ini berusaha didekati oleh Saussure dengan menekankan aspek relasi dari elemen-elemen bahasa dalam suatu struktur, yang disebut sinkroni, yang sekaligus menandai pergeseran studi linguistik dari yang semula berorientasi pada perubahan elemen bahasa secara historis yang disebut diakroni. Dia menganalogikannya sebagai memotong pohon yang benar adalah secara melintang, bukan dari atas ke bawah. Dengan sinkroni, Saussure memperlihatkan bahwa aspek pencerapan elemen-elemen bahasa bukan dipusatkan pada masing-masing entitas bahasa tetapi pada relasinya dengan entitas yang lain. Ia membagi relasi ini secara fundamental menjadi dua, yaitu di tingkat fonetik (dicontohkan dengan coal/call) dan di tingkat fonemik (dicontohkan dengan tin/kin). Dengannya perbedaan entitas-entitas bahasa disistematisasi dalam kaidah oposisi biner sehingga makna-maknanya yang berbeda dapat dilekatkan. Tetapi oposisi biner ini tetap saja menimbulkan kearbitreran petanda terhadap penanda yang tak terselesaikan. Sejauh ini yang dapat disimpulkan hanyalah bahwa perubahan fonetik dan fonemik yang unik dalam entitas-entitas suatu struktur bahasa merupakan ciri dasar dari petandanya yang merupakan abstraksi murni.
Di sisi yang lain konsep oposisi biner yang konstruknya diinterpretasi terlampau sederhana dan dapat ditemukan 'dengan mudah' pada entitas-entitas bahasa ini telah mengundang kecurigaan Derrida bahwa proyek metafisika lama akan dihidupkan kembali. Dalam periode yang cukup panjang metafisika barat telah jatuh pada fundamentalisme dan membakukan serangkaian prinsip final yang 'membunuh subjek'. Bagi Derrida "Semua metafisikawan membentuk dari yang asal, tampak sederhana, utuh, normal, murni, standar, dan mengenal diri. Demi menyembuhkannya dari kecelakaan, penurunan, kesukaran, kemerosotan. Membuat yang baik di depan yang buruk, positif di atas negatif, murni di atas najis, sederhana di atas rumit, dan sebagainya. Ini bukan sekadar gejala metafisikal. Di antara yang lain, ini keadaan darurat metafisika, prosedur paling konstan, mendalam, dan kuat."
Dalam hal di atas Derrida benar dan ia waspada terhadap penarikan kaidah metafisika sederhana yang digeneralisasi dan seolah dapat menjelaskan setiap tanda. Tetapi hingga kini Saussure sendiri belum pernah mengajukan satu contohpun tentang petanda (signified) dari suatu tanda meski dengan gegabah ia menyimpulkan pembentukannya sebagai arbitrer. Tidak pernah dapat dijelaskan misalnya, konsep apakah yang menyebabkan pohon dapat diberi penanda (signifier) tree. Meski kaidah oposisi biner ini bukanlah jawaban metafisika, cara-cara Derrida menggoyahkannya secara liar hingga melepaskan keterpukauan orang pada tanda. Pengertian bahwa nilai sebuah tanda ditentukan sepenuhnya dari perbedaannya dengan tanda-tanda yang lain terwadahi dalam konsepnya yaitu différance. Namun konsep tersebut juga menegaskan bahwa nilai sebuah tanda tidak dapat hadir seketika. Nilainya terus ditunda (deffered) dan ditentukan – bahkan juga dimodifikasi – oleh tanda berikutnya dalam satu aliran sintagma. Différance, karena sifat alaminya, menolak setiap upaya untuk menghentikan alirannya. Derrida seolah hendak mencegah siapapun pada proyek-proyek pencarian penanda (signified) yang sejak semula memang telah dianggap arbitrer, dan bahkan kaidah oposisinya sendiri dengan segera hanyut dalam aliran sintagma.
Dekonstruksi radikal yang ditawarkan oleh Derrida sebenarnya hanyalah untuk membuat batas-batas pengaman yang kokoh dari daya khayal yang menyeruak di dalam benak setiap kali pikiran kita dibanjiri oleh persepsi indrawi. Setiap saat hal itu terjadi maka kaidah filsafat, ideologi dan prinsip kategorisasi apapun menjadi tak berarti; dan daripada menimbulkan keterpukauan, ia lebih baik didekonstruksi. Konsep yang menjadi penanda, yang lebih baik tetap tak terungkapkan daripada diungkapkan secara arbitrer itu, semestinya tetap menjadi bagian dari 'logos'-nya Plato. Dalam The Republic, Plato menjelaskan bahwa 'logos', dipadukan dengan 'musike', sebagai satu-satunya penjaga yang aman untuk 'arete'. Padahal kita tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang ketiganya bila tidak menyelidik langsung ke teks asli dimana istilah tersebut dikonseptualisasi.
Aretè yang sering diterjemahkan menjadi kebajikan (virtue) yang digunakan dalam bentuk tunggal maupun plural. Aretè berarti menjadi baik pada sesuatu, dan adalah sudah lumrah apabila orang Yunani bertanya "aretè dari apa atau siapa?" yang secara sepintas seringkali dipahami orang sebagai 'efisiensi'. Pada abad kelima muncul para guru Sofis yang juga mengajarkan aretè namun belum dalam pengertian etis sebagaimana yang dikemukakan oleh Socrates, Plato, ataupun Aristoteles, dimana mereka merubahnya menjadi kata sifat anthropine yaitu sebuah keunggulan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Namun mereka pun menekankan bahwa pada kenyataannya kebanyakan manusia tidak mengetahui aretè tersebut, dan oleh karena itu manusia harus mencari serta menemukan ergon (amal)-nya sehingga manusia dapat mengetahui apa keunggulannya di muka bumi ini.
Socrates dan Plato, misalnya, menegaskan bahwa hanya segolongan orang saja yang harus ditugaskan untuk melakukan perang, yaitu para hylakes (dalam bahasa Yunani yang berarti penjaga-penjaga), yang dipilih hanya berdasarkan "bakat" tanpa mempertimbangkan asal-usul keturunan, menunjukkan eksistensi kemisian yang unik, yang dikenal sebagai aretè dan hanya dapat diketahui secara utuh bersamaan dengan pencapaian eudaimonia. Keunikan misi hidup ini diilustrasikan dengan indah oleh Plato dalam definisinya tentang keahlian seorang negarawan dengan seorang tukang tenun. Menurut Plato, tugas seorang negarawan sebagaimana halnya tukang yang menenun benang wol menjadi sehelai kain, adalah bertugas menenun, atau menciptakan keselarasan yang harmonis, di antara semua keahlian lain di dalam negara. Secara implisit Plato hendak menunjukkan bahwa dimanapun jalur kemisian hidup seseorang dijalankan, pada hakekatnya tak ada satupun yang dapat dianggap lebih utama dibanding yang lain. Dalam hal ini kata aretè ini dapat dipadankan dengan dharma yang ada dalam agama Hindu.

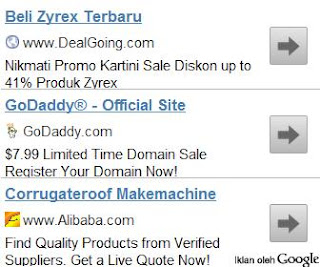
0 comments:
Post a Comment